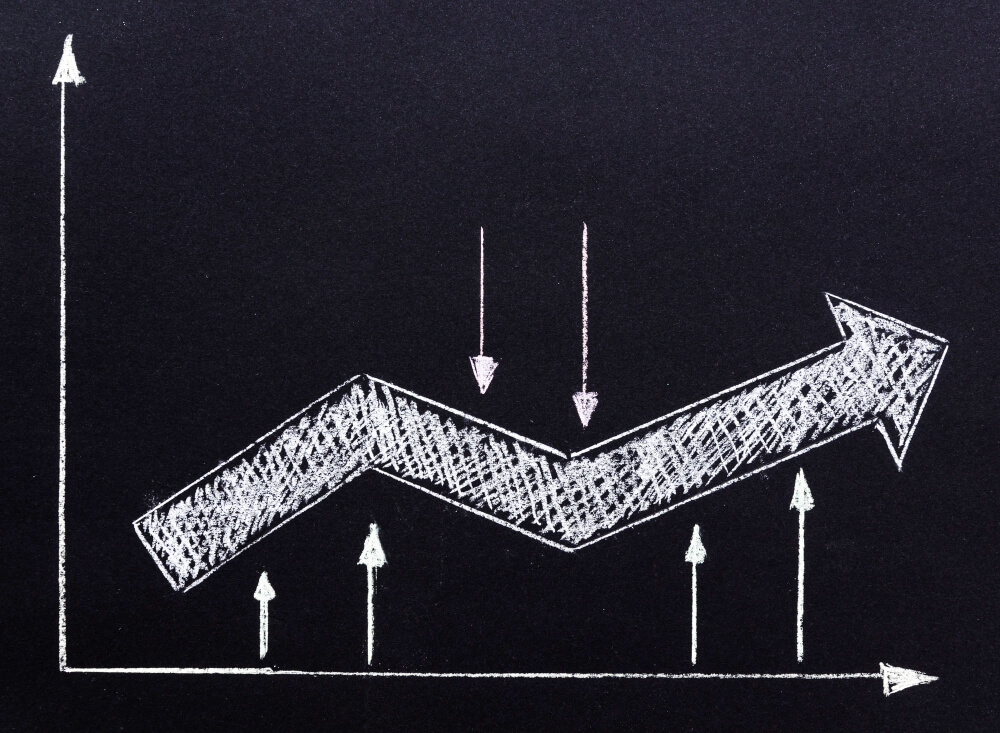Ketika harga-harga barang naik tapi gaji nggak ikut naik, usaha makin sepi, dan cari kerja makin susah—kamu mungkin sedang menghadapi salah satu kondisi ekonomi yang paling bikin frustasi: stagflasi. Istilah ini mungkin terdengar rumit, tapi dampaknya bisa terasa langsung di kehidupan sehari-hari. Yang bikin tambah rumit, stagflasi bukan cuma soal inflasi doang atau ekonomi yang melambat, tapi kombinasi keduanya ditambah tingkat pengangguran yang tinggi. Nah lho, ribet, kan?
Di artikel ini, kita bakal kupas tuntas apa itu stagflasi, dari pengertian dasar sampai ke penyebabnya yang cukup kompleks. Kita juga akan bahas kenapa kondisi ini bikin para ekonom dan pemerintah kelabakan, contohnya dalam sejarah, dan strategi apa saja yang bisa dilakukan buat menghadapi badai ekonomi ini.
Apa Itu Stagflasi?
Stagflasi adalah gabungan dari dua kondisi ekonomi yang biasanya nggak terjadi bersamaan: stagnasi ekonomi dan inflasi. Kalau dibongkar dari kata-katanya, “stag” berasal dari stagnation (alias pertumbuhan ekonomi yang lambat atau mandek), sementara “flasi” berasal dari inflation (kenaikan harga barang dan jasa).
Nah, secara lengkap, stagflasi adalah situasi di mana ekonomi mengalami inflasi tinggi, pertumbuhan ekonomi yang melambat, dan tingkat pengangguran yang meningkat secara bersamaan. Tiga kondisi ini biasanya muncul secara terpisah. Misalnya, saat inflasi tinggi, biasanya ekonomi lagi panas-panasnya—lapangan kerja banyak, konsumsi naik, dan pertumbuhan pesat. Tapi dalam stagflasi, semua logika itu kayak dibalik. Harga naik, tapi ekonomi malah lesu, dan orang-orang kehilangan pekerjaan. Inilah yang bikin stagflasi dianggap sebagai salah satu kondisi ekonomi paling membingungkan dan menakutkan.
Penyebab Stagflasi
Banyak ekonom setuju bahwa penyebab stagflasi itu lebih kompleks dibanding inflasi biasa. Kalau inflasi bisa “dimainkan” lewat suku bunga atau pengendalian jumlah uang beredar, stagflasi punya sumber masalah yang lebih dalam dan seringkali berasal dari faktor eksternal maupun struktural.
Salah satu penyebab paling umum dari stagflasi adalah supply shock atau gangguan terhadap pasokan barang, terutama barang penting seperti energi. Contoh paling klasik adalah saat harga minyak dunia melonjak tajam. Ketika biaya energi naik drastis, biaya produksi juga ikut naik, yang akhirnya mendorong harga-harga barang naik (inflasi), sementara perusahaan-perusahaan mulai mengurangi produksi dan memberhentikan karyawan (pengangguran meningkat).
Selain itu, kebijakan ekonomi yang tidak seimbang juga bisa jadi pemicu. Misalnya, kalau pemerintah terlalu agresif mencetak uang untuk membiayai defisit anggaran, uang beredar jadi terlalu banyak tanpa dibarengi peningkatan produksi. Hasilnya? Harga-harga naik, tapi perekonomian justru lesu karena kepercayaan pasar menurun.
Faktor lainnya yang sering dianggap sebagai “pupuk” bagi stagflasi adalah ekspektasi inflasi. Ketika masyarakat, pelaku bisnis, dan investor mulai terbiasa dengan inflasi tinggi, mereka akan mulai menyesuaikan perilaku—seperti menuntut kenaikan upah, menaikkan harga jual, atau mengalihkan investasi ke aset-aset aman. Efek domino ini bisa memperparah inflasi, meskipun ekonomi sebenarnya lagi dalam kondisi lemah.
Nggak ketinggalan, ketidakpastian global seperti konflik geopolitik, pandemi, atau gangguan rantai pasok global juga bisa mempercepat datangnya stagflasi. Contohnya, saat perang atau ketegangan politik menyebabkan gangguan pada perdagangan internasional, harga bahan baku bisa naik drastis, dan efeknya menjalar ke seluruh sektor.
Kenapa Stagflasi Sulit Diatasi?
Nah, ini bagian yang bikin kepala para ekonom pusing tujuh keliling. Dalam teori ekonomi, cara mengatasi inflasi adalah dengan menaikkan suku bunga, mengurangi belanja, dan memperketat jumlah uang beredar. Tapi di sisi lain, kalau ekonomi lagi stagnan dan pengangguran tinggi, justru yang dibutuhkan adalah kebijakan sebaliknya—yakni stimulus fiskal atau moneter yang bisa mendorong pertumbuhan.
Jadi, dalam situasi stagflasi, pemerintah dan bank sentral kayak terjebak di antara dua pilihan yang sama-sama pahit. Kalau mereka terlalu fokus menurunkan inflasi, misalnya dengan menaikkan suku bunga, maka konsumsi dan investasi bisa makin melemah. Tapi kalau mereka terlalu longgar untuk mendorong pertumbuhan, inflasi bisa makin liar.
Kondisi seperti ini menuntut pendekatan yang sangat hati-hati dan strategis. Nggak bisa asal pilih satu solusi, karena bisa memperparah sisi lain dari masalah. Makanya, stagflasi sering dianggap sebagai “jalan buntu kebijakan”.
Contoh Stagflasi dalam Sejarah
Contoh paling terkenal dari stagflasi adalah yang terjadi di Amerika Serikat pada tahun 1970-an, khususnya setelah krisis minyak tahun 1973. Saat itu, negara-negara anggota OPEC (Organisasi Negara Pengekspor Minyak) memutuskan untuk menghentikan ekspor minyak ke negara-negara pendukung Israel dalam Perang Yom Kippur. Dampaknya luar biasa. Harga minyak melonjak drastis, bahkan sampai empat kali lipat dalam waktu singkat.
Efek domino dari krisis ini langsung terasa di seluruh dunia. Di Amerika, biaya energi naik tajam, produksi terhambat, harga barang melesat, dan pengangguran meningkat. Ekonomi Amerika yang tadinya kuat mulai tersendat. Inilah awal mula istilah stagflasi muncul dan mulai ramai dibahas.
Kalau bicara Indonesia, meskipun kita belum pernah mengalami stagflasi seberat Amerika di tahun 70-an, tapi ada beberapa masa di mana inflasi tinggi bertemu dengan perlambatan ekonomi dan pengangguran. Misalnya, saat krisis moneter 1998 atau masa awal pandemi COVID-19, kita sempat menghadapi tantangan ekonomi yang punya ciri-ciri mirip, walau belum masuk kategori stagflasi penuh.
Strategi Menghadapi Stagflasi
Lalu, apa yang bisa dilakukan untuk menghadapi kondisi serumit ini?
Pertama, penting untuk menjaga keseimbangan antara kebijakan moneter dan fiskal. Bank sentral harus pintar-pintar mengatur suku bunga agar inflasi tetap terkendali, tapi tanpa mematikan pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, pemerintah juga harus lebih selektif dalam belanja—fokus pada sektor-sektor produktif yang bisa menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan daya beli masyarakat.
Diversifikasi sumber energi juga jadi langkah penting, terutama untuk negara yang sangat bergantung pada komoditas tertentu. Kalau harga minyak dunia naik, negara dengan sumber energi alternatif lebih siap menghadapi guncangan.
Langkah berikutnya adalah mendukung sektor UMKM dan inovasi. Di masa stagflasi, UMKM bisa jadi penopang penting karena mereka fleksibel dan bisa cepat menyesuaikan diri. Inovasi juga bisa membuka peluang-peluang baru yang sebelumnya nggak terlihat.
Yang nggak kalah penting adalah membangun kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Ketika masyarakat yakin bahwa pemerintah punya arah yang jelas dan strategi yang masuk akal, mereka cenderung lebih tenang dan nggak terburu-buru mengambil keputusan ekonomi yang bisa memperburuk keadaan.
Penutup
Stagflasi adalah kondisi ekonomi yang langka tapi sangat serius, di mana inflasi tinggi, pertumbuhan ekonomi melambat, dan pengangguran meningkat—semuanya terjadi bersamaan. Kondisi ini menjadi tantangan besar karena solusi untuk mengatasi satu masalah bisa memperburuk masalah lainnya. Penyebabnya pun beragam dan kompleks, mulai dari krisis energi, kebijakan ekonomi yang kurang tepat, hingga ketidakpastian global.
Sejarah mencatat bahwa stagflasi pernah melanda negara-negara besar seperti Amerika Serikat pada tahun 1970-an, dan dampaknya terasa luas. Meskipun sulit diatasi, stagflasi bukanlah situasi tanpa harapan. Dengan strategi yang seimbang, pengelolaan kebijakan moneter dan fiskal yang hati-hati, serta dukungan dari sektor produktif seperti UMKM dan inovasi, dampaknya bisa dikendalikan.
Memahami stagflasi bukan cuma urusan para ekonom atau pembuat kebijakan. Sebagai masyarakat, kita juga perlu melek terhadap situasi ini supaya bisa lebih siap dan bijak menghadapi tantangan ekonomi di masa depan. Karena dalam ekonomi, seperti dalam hidup, semakin kita paham masalahnya, semakin besar peluang kita untuk menemukan jalan keluarnya.